Candi Kedaton, Jejak Sunyi Majapahit di Lereng Tiris
Bacatrend, Probolinggo – Di tengah lanskap hijau Desa Andungbiru, Kecamatan Tiris, Probolinggo, berdiri sebuah jejak masa silam yang nyaris terlupakan: Candi Kedaton. Bangunan ini bukan sekadar tumpukan batu andesit yang tersisa dari masa lalu, melainkan saksi bisu dari peradaban Majapahit yang pernah menjadikan kawasan ini sebagai pusat spiritual dan budaya Hindu Syiwa. Meski bentuknya kini hanya berupa batur atau kaki candi tanpa badan dan atap, pahatan tahun 1292 Saka (1370 Masehi) yang terukir di tangga sebelah kiri menjadi penanda kuat bahwa Candi Kedaton dibangun pada masa keemasan Majapahit.
Candi Kedaton memiliki dimensi yang relatif kecil—sekitar 6 x 6 meter dengan tinggi 2,05 meter—namun nilai sejarahnya jauh melampaui ukurannya. Bangunan ini menghadap barat laut, arah yang tidak lazim bagi candi-candi di Jawa, dan diduga mengarah ke Gunung Semeru atau puncak Gunung Hyang, simbol spiritualitas dalam kepercayaan Hindu. Di sekelilingnya, relief yang terpahat di tiga sisi candi menyimpan kisah-kisah epik: Arjunawiwaha di sisi barat, Garudeya di selatan, dan Bhomantaka di timur. Ketiganya menggambarkan perjuangan spiritual, pengorbanan, dan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan—tema yang erat dengan ajaran Hindu Syiwa1.
Menurut penelitian lokal dari Universitas Pendidikan Ganesha, struktur Candi Kedaton menunjukkan bahwa kawasan ini dulunya merupakan kompleks pertapaan atau kediaman bangsawan Majapahit. Dusun Kedaton sendiri berarti “kerajaan” atau “singgasana”, mengindikasikan status istimewa kawasan ini sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan, termasuk Dyah Wiyat dan Dyah Gayatri, dua tokoh perempuan penting dalam silsilah Majapahit. Penemuan artefak seperti gerabah, arca batu andesit, keramik asing dari Dinasti Ming dan Yuan, mata uang kepeng, serta kerangka manusia—empat perempuan dan satu laki-laki—menambah lapisan misteri dan nilai arkeologis situs ini4.
Salah satu elemen paling menarik dari kompleks ini adalah Sumur Upas, yang terletak di tengah situs. Airnya dipercaya mengandung racun yang dapat merusak sistem saraf manusia, dan hanya digunakan untuk merendam pusaka. Sumur ini juga diyakini sebagai tempat pelatihan ksatria dan konon terhubung dengan lautan selatan melalui lorong bawah tanah. Kepercayaan lokal menyebutkan adanya dhanyang berupa kala raksasa menyerupai kalajengking yang menjaga lorong-lorong candi, memperkuat aura mistis yang menyelimuti tempat ini4.
Dari perspektif arkeologi lanskap, studi adaptasi lingkungan oleh Siregar Sondang Martini menunjukkan bahwa penempatan Candi Kedaton di dataran tinggi dengan elevasi 8,5 meter dan kemiringan 8–13% bukanlah kebetulan. Masyarakat masa lalu memilih lokasi ini secara strategis untuk menghindari banjir dari Sungai Batanghari, menciptakan sistem drainase dan cadangan air bersih yang menunjukkan kecerdasan ekologis mereka. Penelitian geofisika menggunakan Ground Penetrating Radar juga mengungkap adanya struktur bawah tanah yang saling tumpang tindih, memperkuat dugaan bahwa kawasan ini dulunya merupakan pusat permukiman dan aktivitas spiritual6.
Kini, Candi Kedaton dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI Provinsi Jawa Timur dan menjadi bagian dari narasi besar tentang warisan Majapahit yang tersebar di berbagai titik Jawa Timur. Meski akses menuju lokasi cukup menantang, dengan jalan makadam dan setapak sempit, daya tarik sejarah dan spiritualitasnya tetap memikat para peneliti, peziarah, dan pencinta budaya. Di tengah kerusakan dan hilangnya bagian-bagian candi, semangat pelestarian terus tumbuh, menjadikan Candi Kedaton bukan hanya sebagai situs arkeologi, tetapi juga sebagai ruang refleksi tentang identitas, kepercayaan, dan kebijaksanaan leluhur yang tak lekang oleh waktu.






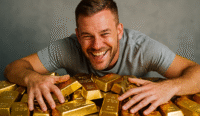






Tinggalkan Balasan